Oleh: Emha Ainun Nadjib
Ada beberapa respons manusia ketika orang lain mencuri hartanya, harta bersama, atau harta Negara. Pertama, respons materiil. Eman hartanya hilang. Tak bisa terima. Alasannya, pemilikan atas harta itu sendiri. Kalau yang dicuri itu harta bersama, misalnya harta rakyat atau negara, ketidakterimaan atas pencurian itu didasari oleh menjadi berkurangnya kekayaan negara.
Kedua, respons keadilan. Tak bisa merelakan perampokan itu dengan alasan seharusnya harta dibagi bersama, tidak boleh ada yang enak sendirian. Kaya atau miskin tak masalah, asalkan atas dasar hak bersama.
Ketiga, respons moral. Mencuri itu merusak nilai kemanusiaan dan menghancurkan kehidupan. Setiap manusia memiliki kewajiban yang sama untuk menghindarkan atau menghalangi pencurian, atas harta siapapun, tanpa ada kaitannya dengan kepentingan diri sendiri atas harta. Yang utama diselamatkan adalah ”orang mencuri”, bukan ”harta dicuri”. Para pencuri harus ditolong dan diselamatkan kemanusiaannya, dengan cara ditangkap dan dihukum. Korupsi itu salah, menghukum koruptor itu benar, membiarkan korupsi itu salah-kuadrat.
Keempat, semacam respons sufistik-dialektis, yang berpedoman pada, dan meyakini pandangan Tuhan bahwa setiap kebaikan akan kembali kepada (menjadi manfaat bagi) pelakunya, demikian juga setiap kejahatan akan berbalik (menjadi bencana yang) menimpa penjahatnya. Lebih dari itu, diyakini juga bahwa kejahatan akan berbuah kebaikan pada yang dijahati.
Ada kalimat kun madhluman wa la takun dhaliman, jadilah orang yang dianiaya, jangan menjadi orang yang menganiaya. Lebih beruntung dirampok daripada merampok. Memfitnah itu rugi besar, difitnah itu berkah. Semakin disengsarakan, semakin terjamin kebahagiaan. Setiap kejahatan yang ditimpakan adalah investasi keuntungan bagi yang ditimpa kejahatan.
Respons jenis ini bisa diekstremkan: semakin penipu yang memerintah, semakin cerah masa depan rakyatnya. Semakin banyak koruptor, semakin terjamin rezeki anak cucu. Pilihlah pemimpin negara yang seburuk mungkin. Bangunlah pemerintahan yang sekorup mungkin. Kalau hari ini tingkat budaya korupsi mungkin mencapai 70%, selayaknya ditingkatkan menjadi kalau bisa sampai 95% ke atas.
Keenam, saya eufemisasikan: respons pertapa. Jiwa pertapa duduk bersila dalam keheningan individual, tidak bisa disentuh oleh riuh rendah urusan negara dan gegap gempita korupsi. Pertapa duduk hening dalam kekhusyukan jiwanya sendiri. Ia kuat dan tangguh. Tidak terpesona dan tidak tergoda. Tidak tergiur oleh kebaikan dan tidak tertekan oleh kebusukan di luar dirinya. Kasak kusuk tentang orang mencuri, merampok, dan korupsi itu mubazir. Itu semua tidak penting ada atau tiada. Sebab pertapa sangat mandiri dengan konsentrasi mental dan kejiwaannya sendiri.
Saya ”bersangka baik” mayoritas rakyat kita adalah jenis ini. Para pertapa menenggelamkan diri di ruang pertapaan pekerjaannya masing-masing. Di sawah-sawah, warung-warung, di ruko-ruko, di jalanan. Di ruang gelap egosentrismenya sendiri-sendiri, di kepulan asap khayalannya, imaji-imaji subjektifnya, dalam persangkaan dan anggapan-anggapannya masing-masing. Yang di luar itu -orang lain, masyarakat, Negara, undang-undang, aturan-aturan- tidak penting-penting amat, kecuali ketika kongkret, dan langsung memberinya keuntungan atau kerugian.
Pertapa juga tidak terusik jika orang menyebutnya bodoh, buta sosial, a-politis, mata kuda, tidak punya wawasan, tidak mengerti bahwa ia sedang dizalimi, tidak peduli ada kemaslahatan bersama, atau diklaim apapun berdasarkan nilai atau terminologi yang bagaimanapun.
Keenam, asal-asalan saja kita sebut respons reformasi. Reformasi Indonesia yang bergulir mulai 1998 sedang mengalami evolusi yang mungkin sangat panjang. Tahapnya sekarang, dalam konteks korupsi: ”Kamu jangan korupsi. Maksud saya, jangan hanya kamu yang korupsi. Gantian. Saya juga ingin.” Reformasi melapangkan dan melebarkan jalan korupsi, mematangkan orde korup menuju era korupsi absolut. Korupsi adalah hak asasi setiap manusia. Ekspresi kebebasan makhluk hidup. Potensi korupsi sudah tersedia sangat melimpah dalam kebudayaan masyarakat. Spirit korupsi sudah bersemai sejak dari cara berpikir, menyusun niat, melangkah bekerja di bidang apapun.
Hamparan luas dan tekstur demokrasi juga tak bisa menghindar untuk mengandung lobang-lobang yang bisa dimanipulisai pelakunya untuk melakukan korupsi, asalkan tidak ketahuan. Dan supaya kemungkinan ketahuan bisa diminimalisasi, maka korupsi sebaiknya dilakukan secara berjamaah, dengan saf-saf yang rapat, agar tidak bisa diisi oleh setan-setan yang tidak terbuat dari sesama manusia: minal jinnati wan-nas. ”Saya aktivis andalan, sudah puluhan kali demo dan ratusan kali orasi revolusi: awas kalau saya nggak jadi komisaris perusahaan ini atau itu. Minimal jadi staf ahli presiden atau wakil menteri, sekurang-kurangnya direkayasa menang tender proyek-proyek.”
“Martabat politik dan nilai dasar perjuangan saya adalah kepiawaian memilih karier, yakni numpang partai politik yang menang.” Rakyat menghormatinya, mengaguminya, mengidolakannya, mencium tangannya, mengangkatnya sebagai pejabat sangat tinggi, ternyata maling.
Korupsi uang dan harta, korupsi waktu, korupsi identitas, korupsi berupa pemalsuan atau lazim disebut pencitraan, korupsi peluang-peluang, korupsi kedaulatan dan kewenangan, korupsi huruf, kata dan makna, korupsi jebakan pasal undang-undang. Atau korupsi tipu daya konstitusi yang menutup kemungkinan manusia sejati nasionalis sejati menjadi pemimpin. Korupsi tafsir, korupsi informasi, berbagai-bagai jenis dan wilayah korupsi –sudah menjadi habitat primer bangsa kita.
Dan dalam keadaan separah itu, sekarang kita berangkat ke 2014 tetap dengan mempercayai apa-apa dan siapa-siapa yang sudah terbukti sangat merusak untuk tetap dipercaya, serta tetap memakai perangkat-perangkat nilai dan formula yang sudah jelas sangat menghancurkan untuk terus dipakai. Untunglah kita tak henti teriakkan ”supremasi hukum”, sebagai cerminan bahwa yang mengepung kita adalah kenyataan pelanggaran hukum. Dan di antara sekian banyak jenis pelanggaran hukum, yang unggul dan menang adalah “supremasi korupsi”.
Kita semua anti-korupsi, meskipun anti-korupsi tidak pasti sama dengan tidak suka korupsi. Kalau kita ketahuan korupsi, ditangkap, diadili, dan dipenjarakan – kita sangat menyesal kenapa kurang rapi mengatur kegemaran utama kita itu sehingga tertangkap.
Korupsi itu cenderung menyenangkan. Sehingga orang yang berani tidak melakukannya, tergolong memiliki derajat kemanusiaan yang tinggi. Di bulan Ramadan aslinya enak tidak berpuasa daripada berpuasa: maka tinggilah derajat orang yang rela berpuasa. Berpuasa adalah ikhlas tidak melakukan sesuatu yang ia sukai, atau rela melakukan yang tidak disukai.
Baru hari ini saya menyadari bahwa jaman edan Pujangga Ronggowarsito bukanlah kisah tentang zamannya, melainkan keadaan dua abad sesudah era beliau. ”Amenangi jaman edan, Ewuh aya ing pambudi, Milu edan nora tahan, Yen tan milu anglakoni, Boya kaduman melik, Kaliren wekasanipun….” Dalam ungkapan sehari-hari orang menuturkan ”amenangi jaman edan, yang tidak ikut edan tidak kebagian, dan pasti kelaparan…”
Kalau situasi kehidupan di era Raden Bagus Burham santri Kyai Kasan Besari Ponorogo, 1802-1844, disebut jaman edan: apa sebutan yang sepadan untuk tingkat sangat tinggi keedanan Indonesia 2013? Sayang sekali kalimat ”kalau tidak ikut edan, tidak akan kebagian sehingga menjadi kelaparan” sangat merasuk dan dipercaya oleh masyarakat. Sehingga ”yang tidak takut tidak kebagian” jumlahnya sangat minimal. Maka, yang paling realistis menggapai sukses adalah korupsi, baik karena kemelaratan maupun karena keserakahan.
Teknologi peradaban korupsi sejak tahap niat hati, dan cara berpikir otak. Kemudian diaplikasikan pada setiap langkah kaki dan gerak tangan, di wilayah keuangan sampai pun agama dan perhubungan dengan Tuhan. Kosakata paling dasar yang dikorupsi adalah ”akal”. Puluhan kali Tuhan menyindir ”Apakah kalian tidak mengakali? Afala ta’qilun?.” Makna mengakali adalah memperlakukan sesuatu dengan kecerdasan dan kreativitas akal, sehingga hutan menjadi sawah dan kebun, tanah menjadi batu-bata, kapas menjadi pakaian, kayu menjadi rumah, logam menjadi pesawat, bunyi menjadi lagu, ketela menjadi kripik, tepung menjadi roti, bayi menjadi manusia dewasa.
Kita korup makna “mengakali” menjadi berarti meliciki, mencurangi, mengelabuhi, menipu-daya. Akal satu-satunya unsur anugerah Allah yang membuat manusia menjadi benar-benar manusia, sudah kita eliminasi substansinya. Maka Tuhan menyebut kita ”ulaika kal-an’am, bal hum adholl’: mereka layaknya hewan, bahkan lebih hina dari itu.
Modernisasi kehidupan juga tidak membuat manusia mampu membedakan “uang”, “gaji”, “pendapatan”, “laba” dengan “rezeki”. Orang berebut uang, memperjuangkan kenaikan gaji, mengakali peningkatan pendapatan, merundingkan marking-up laba, karena menyangka itu semua sama dan sebangun dengan rezeki. Manusia tidak mendayagunakan ilmunya untuk mengkreatifkan, dan mengeksplorasi kemungkinan sumber-sumber rejeki yang Tuhan sendiri merumuskannya dengan idiom ”min haitsu la yahtasib”: berasal dari mata air yang tak diperhitungkan, yang tak terduga, yang tak hanya terbatas pada lajur-lajur lembar akuntansi.
Seorang Ki Ajar, guru masyarakat, kalau kebun-kebun buahnya panen, mempersilahkan masyarakat dan siapa saja terlebih dahulu mengambilinya, kemudian beliau mengais sisa-sisanya untuk diri dan keluarganya. Sesudah itu ribuan peristiwa ”min haitsu la yahtasib” membuat Ki Ajar tetap saja merupakan orang terkaya di daerahnya. Seorang maula ditanya oleh malaikat, ”Kenapa kamu tidak ikut berebut harta, karier, jabatan, peluang, asset, akses, sebagaimana semua rekan-rekanmu?” Dijawab, ”Saya tidak tega karena kemungkinan besar saya menang dalam persaingan dan perebutan. Jadi saya memilih jadi pembantu rumah tangga Tuhan saja, terserah beliau menyuruh saya melakukan apa.”
Karena orang tidak mau belajar, malas meneliti, tidak tekun berlatih, serta tidak berani ambil risiko mengaplikasikan ”min haitsu la yahtasib”, maka pilihan utama hidupnya ialah menghimpun cara dan strategi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, dengan modal sekecil-kecilnya. Bisa dengan menciptakan secara eksklusif ”etika perekonomian dan industri” yang permisif terhadap substansi etika yang sebenarnya. Bisa dengan manipulasi aturan. Bisa dengan penipuan wacana-wacana dalam retorika keusahaan. Tapi yang paling pragmatis adalah korupsi. Korupsi itu dilakukan diam-diam dan tidak jantan. Levelnya sama dengan pengutil atau pencopet. Kalah terhormat dibandingkan dengan perampok atau penjambret.
(Dimuat di Majalah Gatra Edisi 18 / XIX 13 Maret 2013)

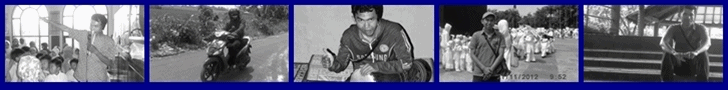
.jpg)
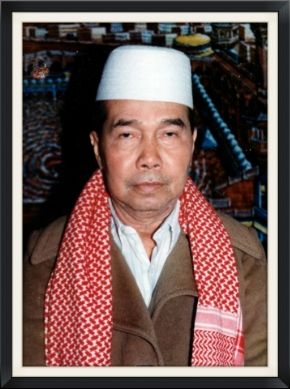
.jpg)

.jpg)





0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !